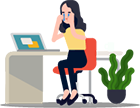Lirih Harap Batu-Batu
Oleh Fadillah Tri Aulia

Mesilina masih belum beranjak dari batu besar tempat mencuci pakaian di sungai. Padahal, pakaian-pakaian kotor yang dibawanya tadi sudah bersih tertumpuk di batu sebelahnya. Rambut panjangnya pun sudah hampir kering oleh angin. Ia justru sibuk melempar batu-batu kecil ke sebuah ceruk kecil di tepi sungai dengan tatapan yang kosong.
“Hoi, jangan melamun nanti kena tesafo!” gadis di sebelahnya mengingatkan.
Ah, demi mendengar tesafo, Mesilina pun bergegas memungut sebuah batu. Ia bangkit, mengambil tumpukan pakaian bersihnya, dan melangkah meninggalkan sungai. Ia sering melihat orang-orang kena tesafo. Ia ingat betul bagaimana ekspresi orang-orang saat mengalami tesafo, dirasuki makhluk gaib.
“Hei, tunggu aku!” gadis yang mengingatkannya tadi setengah berlari mengejar Mesilina.
“Bukannya kau sendiri yang ingatkan aku untuk cepat-cepat, Lisa?” ujar Mesilina sambil memperlambat langkahnya.
“Ah, kau ini bisa saja membalikkan keadaan. Memang benar apa kata Pak Guru Adam, kau anak pintar.”
Mesilina menghentikan langkahnya. Bagaimanapun, nama yang baru saja didengarnya tadi memiliki pengaruh tersendiri dalam pikirannya. Sosok itulah yang kerap kali datang dan membuat Mesilina melamun memikirkan banyak hal, hal-hal yang tak pernah ia mampu pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang menurutnya tidak perlu ia pikirkan sebagai ono niha atau orang Nias, khususnya perempuan pedalaman Nias.
“Hey, bengong lagi kau!” tegur Lisa.
Mesilina pun melanjutkan langkahnya lebih cepat hingga napas Lisa tersengal - sengal agar bisa berjalan sejajar dengannya.
Saat tiba di rumah, Mesilina menjumpai ayahnya sedang berbincang dengan seorang tetua adat. Mereka sedang membicarakan bowo, sejumlah harta, baik berupa uang, babi, maupun barang lain yang harus diberikan keluarga pengantin pria kepada pengantin wanita. Halawa, kakak Mesilina, akan meminang gadis yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Hal itu pula yang turut membebani pikirannya akhir-akhir ini.
Urusan pernikahan merupakan urusan yang sangat pelik di sini. Pelik tak hanya dalam tata caranya, tapi juga harganya. Untuk menikah, setidaknya keluarganya harus menyiapkan puluhan ekor babi, puluhan gram emas, dan puluhan ikat kain. Itu belum termasuk porsi hidangan yang harus disajikan kepada tamu-tamu nanti.
Untunglah, gadis yang akan dinikahi kakaknya berasal dari keluarga biasa saja, bukan keluarga kepala kampung atau tetua adat. Semakin tinggi bosi atau status sosial keluarga gadis itu, maka semakin tinggi bowo yang harus diberikan.

Ama Halawa, ayahnya, hanyalah petani cokelat seperti kebanyakan penduduk di kampung ini. Kalau pun ada babi di belakang rumahnya, jumlahnya bisa dihitung jari. Bagaimanapun, keluarganya harus meminjam sana-sini untuk memenuhi biaya pernikahan itu. Dan begitulah kebersamaan di kampung ini terbangun, dari utang-mengutang. Setiap keluarga punya utang kepada keluarga lain, terkait satu sama lain. Mereka membayarnya saat pesta diadakan.
“Kenapa kau berdiri di pintu? Ayo bantu bibimu di dapur!” seru ayahnya.
Mesilina bergegas menuju dapur. Asap mengepul tebal di dapur. Bibinya sedang mendidihkan air untuk merebus ubi.
“Ah, untunglah kau sudah pulang. Sudah sore sekali ini,” kata adik ayahnya di sela batuk-batuk yang seakan tak pernah bisa sembuh.
Bagaimana lagi, asap-asap yang terperangkap di dapur mau tak mau harus dihirup perempuan setengah baya itu setiap hari. Mesilina sering menyarankan bibinya untuk makan pisang, jeruk, dan bawang putih. Dari buku yang ia baca, makanan-makanan itu bisa mengurangi batuk yang berkepanjangan.
“Bawalah ini ke ayahmu,” pinta bibinya sambil menyerahkan dua botol tuak yang terbuat dari fermentasi nira atau kelapa. Bagi orang kampung ini, minum tuak sama halnya dengan minum teh atau kopi, sudah jamak sekali.
Dengan langkah gontai Mesilina berjalan menuju ruang depan. Tentu, masih ada ayahnya dan temannya di situ.
“Sudah besar anak gadismu ini rupanya, Ama Halawa,” bisik Ama Sahili, teman ayahnya.
Mesilina risih mendengarnya. Untunglah, ayahnya tak terlalu menghiraukan ucapan Ama Sahili. Ayahnya terlalu sibuk menghitung berapa babi yang harus disiapkannya. Sebenarnya ucapan semacam itu bisa jadi masalah di kampung ini. Perempuan sangat dihormati di sini. Tak ada laki-laki yang berani melecehkan perempuan di sini. Jika ada laki-laki yang berani melecehkan perempuan, baik secara lisan maupun fisik, bisa kena denda. Bahkan lebih rumit, nyawa urusannya. Mesilina pun berpikir, besarnya biaya perkawinan juga menunjukkan betapa mereka sangat menghargai perempuan.
Malam sudah larut, tapi Mesilina masih belum tertidur. Ia masih memikirkan pembahasan di sekolahnya beberapa hari lalu. Pak Guru Adam mengajak anak-anak menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kampungnya. Itu perkara mudah, tentu saja, apalagi bagi anak secerdas Mesilina. Tak banyak jenis pekerjaan di kampung pedalaman ini. Mungkin akan lebih banyak pekerjaan yang bisa disebutkan di kecamatan yang letaknya sekitar 14 kilometer dari sini.
Rupanya pembahasan tak habis di situ. Pak Guru Adam memperkenalkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Guru dari Medan itu membawa banyak kartu bergambar dengan tulisan jenis pekerjaan di bawahnya. Ia bermain kartu itu bersama teman-temannya.
Pak Guru Adam selalu punya cara yang menyenangkan saat mengajar di kelas. Bagaimana lagi, ia harus mencari cara agar murid-murid yang berusia beragam bisa betah dan semangat sekolah. Murid SMP di sini usianya macam-macam, mulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Bangunan sekolahnya menyatu dengan bangunan SD. Kepala sekolah saja hanya datang seminggu sekali pada hari Senin.

Sayangnya, pembelajaran yang menyenangkan itu justru membuat Mesilina berpikir banyak hal. Ia ambil sebuah kartu bergambar yang ia pinta dari Pak Guru Adam. Pulmonologist (dokter spesialis paru-paru), begitu tulisan yang tertera di kartu itu. Melihat gambar itu ia ingat almarhum ibunya yang meninggal dengan batuk berdarah dan sesak napas yang berkepanjangan.
Kata orang-orang kampung, ibunya terkena tesafo karena kelepasan menyebut nama leluhur tanpa membaca doa dan memotong ayam. Namun, dari buku yang ia baca di sekolah, sepertinya ibunya terkena TBC.
Di kampungnya tak ada dokter. Jika ada apa-apa, penduduk kampung akan memanggil Pak Lektor. Ia akan membaca doa-doa agar penyakit yang dibawa roh jahat itu pergi.
“Ah, anak cerdas sepertimu cocok sekali jadi dokter!” kata Pak Guru Adam saat Mesilina menjawab ia ingin jadi dokter.
Namun, nyatanya cerdas saja tak cukup. Harapan itu sepertinya masih terlalu tinggi bagi gadis kampung sepertinya. Jangankan untuk kuliah, izin untuk sekolah setingkat SMA saja sepertinya akan sulit ia dapatkan dari ayahnya. SMA terdekat ada di kecamatan, tapi tetap saja jauh bagi orang-orang kampung ini. Selain jarak, masalah biaya pun jadi kendala. Masih beruntung ia bisa terus sekolah hingga SMP tanpa terputus.
Banyak teman sebayanya yang putus sekolah karena harus bekerja membantu orang tua mereka di ladang cokelat atau jadi penyadap karet. Dan kini, ia pun was-was. Bisa jadi, setelah pernikahan kakaknya, ia harus berhenti sekolah dan membantu ayahnya mengumpulkan uang untuk membayar utang keluarga mereka.
Pak Guru Adam dengan ilmunya telah memberinya harapan-harapan yang baginya hanya ada di dunia luar. Dunia yang sementara ini tak bisa ia raih. Hal itulah yang kadang membuatnya merasa menyesal sekolah. Untuk apa ia bisa tahu banyak hal dan mengharapkan semua hal tersebut, tapi tak ada yang dapat diraihnya.
Namun, ia tetap bersyukur bisa sekolah. Setidaknya, ia bisa melihat dunia luar meski hanya berupa cerita dan gambar. Ia bisa punya mimpi yang dapat menghiburnya saat ia jenuh dengan kerutinan di kampung itu. Ia punya mimpi yang mungkin bisa ia titipkan kepada anak atau cucunya kelak saat semuanya berubah.
Pak Adam pernah berkata bahwa selalu ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari setiap kejadian yang kita temui atau kerjakan, asalkan kita mau menerimanya agar dapat melihat manfaat-manfaat yang tersembunyi di balik semua hal itu.
Mesilina pun teringat percakapannya dengan Lisa di sungai tadi sore.
“Setidaknya, nanti aku tak lagi jadi beban ayah dan ibuku.” Begitu yang dikatakan Lisa ketika merapikan tumpukan pakaian yang baru selesai ia cuci di sungai.

Mesilina tersenyum getir mengingat ‘manfaat tersembunyi’ yang tadi diucapkan temannya itu. Terlintas di pikirannya bahwa Lisa akan menikah di usia muda. Bagaimanapun, menurutnya Lisa masih terlalu muda untuk menikah. Mereka sama-sama baru berusia lima belas tahun. Namun, Mesilina kembali berpikir, apakah ia akan mampu menghindar jika hal itu terjadi pula kepadanya?
Dari celah jendela, Mesilina melihat tumpukan batu yang tiap hari dibawanya dari sungai sehabis mandi dan mencuci sejak usianya tujuh tahun. Batu-batu itu jika sudah terkumpul banyak akan digunakan untuk dijadikan pondasi rumah, meninggikan jalan, dan membuat benteng oleh para lelaki. Mungkin begitulah hidup perempuan di sini. Setiap hari mereka membawa mimpi-mimpi, akan tetapi pada akhirnya mimpi-mimpi itu akan disusun oleh para lelaki. Namun, Mesilina berpikir lain. Mimpi-mimpinya mungkin kelak tak lagi jadi mimpinya sendiri. Mimpi-mimpinya akan menjadi mimpi yang ia harap bisa dibagi dengan suami dan anak-anaknya kelak.
Sebagaimana penduduk Nias lainnya, ia adalah keturunan manusia langit yang tugasnya hanya patuh pada setiap nilai dan aturan agar dapat kembali ke tete holi ana’a, negeri di atas awan, sebagai orang suci. Oleh karena itu, ia tak lupa bahwa natolau atau terus berupaya adalah salah satu nilai yang harus dipegang orang Nias, pun dirinya.
Sebelum tidur, ia simpan buku yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah: Ramuan Obat Tradisional Nusantara.