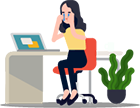Laut dan Gadis Kecil
Oleh: Fadillah Tri Aulia

“Dara, dara yang sendiri
Berani mengembara
Mencari di pantai senja,
Dara, ayo pulang saja, dara
Tidak, aku tidak mau!
Biar angin malam menderu
Menyapu pasir, menyapu gelombang
Dan sejenak pula halus menyisir rambutku
Aku mengembara sampai menemu.”
….
Angin tiba-tiba berhenti bertiup jatuhkan helaian rambutku. Riak gelombang tiba-tiba lenyap hingga air samudera yang mahaluas menyatu dengan ujung kainku. Saat itu, seorang gadis kecil lewat di depanku. Mata bulatnya tepat menatapku. Ada sendu yang berpijar redup di kedua bola matanya yang pekat. Kakinya ragu melangkah, mendekatiku, pun tangannya yang menggantung ragu di sisi badannya yang kurus.
“Ibu?” tanyanya cepat.
Pijar di matanya sedikit berbinar. Mungkin ada tautan memori yang berpilin dengan diriku.
“Apa kau ibuku?” gadis kecil itu bertanya lagi.
Ia melangkah, mendekat. Ada pijar yang semakin membara namun meliuk lembut, tak ada angkara, yang ada cinta. Ya, cinta. Rasa itu membuatku berat untuk menolak dan mengatakan bukan padanya.
Maka sebongkah jawaban kulontarkan, “Tentu, aku ibumu.”
Tubuh kecil itu pun menubrukku. Tangannya lantas melingkari pinggangku. Ada basah yang meresapi kainku hingga terasa hangat di perut. Tanganku yang semula menggantung ragu jadi bergerak memeluk tubuhnya. Aku mengusap rambut hitam kemerahannya yang panjang dan menyisirnya dengan jemariku.
Cukup lama kami begitu. Hanya ada isak yang terdengar, menggema dalam sore yang semakin tua. Kubiarkan isak itu mereda berangsur menjadi sunyi menyisakan tubuh kurusnya yang tersengal.
Ia mencoba menatapku. Bulu matanya melekat satu sama lain karena air mata yang tadi meluap.
“Aku rindu, Bu,” bibirnya yang mungil meruncing.
Entahlah, aku bukan i-b-u-nya, tetapi rindu itu kembali menolakku untuk mengatakannya. Seolah, jika aku mengatakan “bukan” maka seisi dunia akan menatapku tajam. Tega.
“Ah ya, tentu. Kita sudah lama tidak bertemu,” kuusap rambutnya yang lengket oleh keringat.
“Kapan terakhir kita bertemu?”
Kepalanya menggeleng perlahan. “Sudah lama. Sangat lama sekali, Bu,” jawabnya.
Ya tentu sangat lama. Kuatnya rangkulanmu dan lamanya tangismu menyatakan hal yang sama. Ada rindu yang begitu menggebu seperti tanah kerontang yang lama tak diguyur hujan seabad.

Kumenuntunnya duduk berdampingan denganku di atas batu karang. Tangan kurusnya terkunci melingkari pinggangku. Pun kepalanya yang seakan patah-jatuh begitu saja dan melekat di lenganku.
“Bagaimana kabar ayahmu?” Tentu aku tak kenal ayahnya, tetapi entah kenapa aku ingin tahu.
“Ayah?” Gadis itu terdiam sejenak.
“Ayah sudah menyatu dengan gelombang laut. Angin laut selalu membawa pesannya saat pagi datang. Pesan agar aku tetap mencarimu,” lanjutnya.
“Kapalnya rusak diterjang gelombang besar saat sedang mencari ikan di laut. Teman-temannya tak mampu menyelamatkannya, tentu, tak seorang pun mau menolongnya di saat laut begitu murka.”
“Murka?”
“Ya, sepertinya begitu. Laut tak pernah lebih menakutkan daripada hari itu. Sebelumnya, kami bersahabat akrab, sangat akrab, bukannya Ibu tahu? Kurasa semua nelayan pun begitu. Tentu, kami tak pernah menyakiti laut. Kami hanya mengambil sebagian ikan dari laut tanpa harus mengambil lebih,” jawabnya tanpa jeda.
“Begitukah? Lantas, mengapa laut begitu murka?” tanyaku penasaran.
“Itu bukan salah Ayah, Bu. Ayah hanya menggunakan kail dan jala untuk menangkap ikan, sungguh,” gadis itu hampir menangis.
“Aku, eh, Ibu percaya,” kucoba menenangkannya.
“Ya, Ayah orang baik, semua orang tahu itu. Ayah sempat dipilih untuk menjadi kepala para nelayan namun ia menolak. Ia lebih senang melaut daripada mengurusi nelayan yang tak mau ikuti aturan.”
Gadis itu menatap laut datar di hadapannya.
“Mungkin itu yang membuat laut marah,” timpalku.
“Karena nelayan itu?”
“Bukan, ayahmu,” jawabku telak. Tak ada desir yang berani menyela.
“Laut marah karena ayahmu tak mau mengatur nelayan dan orang-orang di pantai ini. Laut percaya ayahmu mampu tetapi ia menolaknya. Lebih senang melaut katanya?”
“Tapi, bu….”
“Ayahmu pura-pura tak mendengar tangis pilu penyu-penyu yang tempurungnya dikuliti. Ia pun pura-pura tuli untuk mendengar tangisan hiu-hiu yang dibiarkan mati setelah siripnya dipotong. Bahkan, tangisan paus-paus yang perutnya penuh dengan plastik itu pun dibiarkannya saja,” ujarku.
“Kau tahu? Ribuan penyu mati setiap tahun gara-gara plastik itu. Bahkan, plastik jahat itu sudah berani memasuki bagian laut terdalam di bumi, Palung Mariana.”
Gadis itu diam.
“Ayahmu hanya ingin melaut saja, katamu? Ya, tentu. Orang-orang lebih senang melaut saja, menikmati semua hasil dari laut tanpa mau berusaha lebih keras untuk menjaganya,” seruku seakan tak mau kalah dengan suara debur ombak yang menerjang tebing-tebing batu di sebelah timur.
Ada ragu dalam tatapan gadis itu. Tangannya mulai lepas dari pinggangku.
“Ayahmu mungkin hanya menggunakan kail dan jala untuk menangkap ikan. Namun, ia biarkan saja teman-temannya menangkap ikan dengan pukat harimau yang begitu menjerat, menangkap semua ikan bahkan yang masih terlalu kecil sekalipun tak dibiarkan lolos.”

Air mataku turun demi mengingat teman-temanku. Aku masih ingat bagaimana mereka mengadu di sela tangisnya yang sendu. Mengadu, apakah ikan-ikan sudah begitu sedikit hingga manusia mencari cara lain untuk mendapat keuntungan dari laut? Apakah perut manusia telah berubah menjadi sebesar perut paus hingga tak pernah puas dengan ikan-ikan yang diberikan laut?
Tak cukup itu. Mereka pun mengadu apakah gelombang ombak menghantam kapal terlalu keras hingga membenturkan kepala manusia lalu lupa untuk berterima kasih pada laut dengan menjaganya? Apakah angin laut sudah terlalu dingin hingga membuat hati manusia membeku? Dan aduan-aduan lainnya.
Begitulah, mereka terus mengadu dan bertanya hingga tak mampu lagi berenang. Maka, pasrahlah mereka dalam pelukanku hingga lenyap jadi buih-buih yang bebas berkelana.
“Jika orang baik tak mau mengatur dan biarkan orang jahat mengatur lantas bagaimana? Hidup bukan hanya tentang dirimu atau orang-orang yang dicintai. Ada tugas yang harus manusia jaga sebagai pemimpin yang Tuhan ciptakan. Ayahmu orang baik maka aku yakin ia tahu itu, amanah itu.” kataku cepat.
Gadis itu kaget. Tatapan matanya berubah.
“Apa kau ibuku?” Gadis itu melepaskan lingkaran tangannya dan menatapku lekat.
“Mungkin,” jawabku.
“Hari sudah semakin senja. Saatnya angin darat membawaku pulang ke samudera,” bisikku sambil beranjak. Namun, tangan mungilnya menarik jemari tanganku.
“Bolehkah aku ikut?”
“Tidak. Kau masih punya tugas untuk menjaga alam ini, menjagaku.”
Ia lepaskan jemariku dan berdiri mematung di belakangku.
“Laut,” ia sebut namaku, “sampaikan salamku pada Ayah.”
Saat kuingin jawab pinta itu dengan sebuah senyuman, gadis itu tak lagi ada di belakangku. Hanya ada seekor elang laut terbang melesat di wajah samudera yang kelam. Lantas, pada siapa kutitipkan diriku?
….
Malam kelam mencat hitam bintang-bintang
Tidak ada sinar, laut tidak ada cahaya
Di pantai, di senja tidak ada dara
Tidak ada dara, tidak ada, tidak.
(Datang Dara, Hilang Dara karya Chairil Anwar puisi terjemahan Song of the Sea karya Hsu Chih Mo)